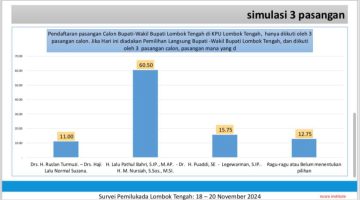dr. Mamang Bagiansah, SpPD., FINASIM
Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya
Ketua IDI Cabang Lombok Tengah
Direktur RSUD Kabupaten Lombok Tengah
Lomboknesi.id- Pemerintah Indonesia sudah mulai memperkenalkan prinsip asuransi pada tahun 1947. Seperti juga yang berkembang dinegara maju, asuransi kesehatan berkembang dimulai dengan asuransi sosial dalam bidang kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pada waktu itu Pemerintah mewajibkan semua perusahaan untuk mengasuransikan karyawannya terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Namun demikian, karena situasi keamanan dalam negeri pasca kemerdekaan yang masih belum stabil akibat adanya berbagai pemberontakan dan upaya Belanda untuk kembali merebut Indonesia, maka upaya tersebut belum memungkinkan untuk terlaksana dengan baik.
Pada tahun 1960 pemerintah mencoba memperkenalkan lagi konsep asuransi kesehatan melalui Undang-Undang Pokok Kesehatan tahun 1960 yang meminta pemerintah mengembangkan dana sakit dengan tujuan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Akan tetapi karena berbagai kondisi sosial ekonomi yang belum kondusif, maka undang-undang tersebut sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Kemudian Pada tahun 1967, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) mengeluarkan Surat Keputusan untuk mendirikan Dana mirip dengan konsep Health Maintenance Organization (HMO) atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang berkembang kemudian guna mewujudkan amanat Undang-Undang Kesehatan tahun 1960 tersebut dan untuk melaksanakannya, Menteri Tenaga Kerja saat itu menetapkan iurannya sebesar 6% upah yang ditanggung majikan sebesar 5% dan karyawan 1%. Sayangnya SK Menaker tersebut tidak mewajibkan perusahaan untuk itu. Akibatnya SK tersebut menjadi tidak berfungsi dan skema asuransi kesehatan tersebut tidak pernah terwujud.
Upaya pengembangan asuransi kesehatan sosial yang lebih sistematis mulai diwujudkan di tahun 1968 ketika Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Awaludin Djainin, mengupayakan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri dan keluarganya. Upaya ini merupakan skema asuransi kesehatan sosial pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Program asuransi ini awalnya dikelola oleh suatu badan di Departemen Kesehatan yang dikenal dengan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan tersebut sebagaimana badan lain yang berada di dalam birokrasi tidak memiliki fleksibilitas cukup untuk merespon tuntutan peserta dan fasilitas kesehatan. Administrasi keuangan di departemen umumnya lambat dan birokratis sehingga tidak mendorong manajemen yang baik dan memuaskan pemangku kepentingan (stake holders). Oleh karenanya Askes kemudian dikelola secara korporat dengan mengkonversi BPDPK menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang dikenal dengan Perum Husada Bakti (PHB) di tahun 1984. Perubahan menjadi PHB membuat pengelolaan Askes, yang pada waktu itu dikenal juga dengan istilah Kartu Kuning, dapat dikelola secara lebih fleksibel. Istilah Kartu Kuning dikenal sejak program dikelola oleh BPDPK karena kartu peserta berwama kuning.
Upaya asuransi sosial dalam bidang kecelakaan kerja juga dimulai dengan didirikannya Perusahaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) pada 1971. Astek pada awalnya hanya menangani asuransi kecelakaan kerja. Upaya perluasan program asuransi sosial menjadi program jaminan sosial yang lebih lengkap dimulai dengan uji coba Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja (JPK Jamsostek) di lima propinsi yang mencakup sekitar 70.000 tenaga kerja di tahun 1985. Uji coba selama lima tahun dimaksudkan untuk menilai kelayakan memperluas asuransi kesehatan sosial ke sektor swasta yang memiliki ciri berbeda dengan sektor publik (Askes).
Di bulan Februari 1992, Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) disetujui DPR yang mencakup empat program jaminan sosial yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian.
Program JPK menerapkan program asuransi sosial yang jaminannya diberikan juga kepada anggota keluarga karyawan, sedangkan ketiga program jaminan sosial lainnya hanya diberikan kepada karyawan. Program JHT, di lain pihak, merupakan program tabungan, bukan program asuransi. Asuransi sosial kesehatan pegawai swasta memiliki kekuatan hukum yang lengkap dibandingkan dengan Askes PNS yang tidak didukung sebuah UU.
Dalam perkembangannya, program JPK ternyata tidak dijalankan secara konsisten, karena pada Peraturan Pemerintah nomor 14/1993 dibolehkan firma tertentu keluar atau tidak ikut JPK Jamsostek (opt out). Paket jaminan JPK Jamsostek pun tidak menjamin hemodialisa, pengobatan kanker, bedah jantung dan kelainan bawaan. Padahal, justru pengobatan yang mahal tersebut yang dibutuhkan karyawan. Klausul pasal inilah yang menyebabkan cakupan peserta program JPK Jamsostek tidak pernah besar dan sampai pada tahun 2012 hanya sekitar 2 juta tenaga kerja atau sekitar 6 juta tertanggung yang mendapatkan perlindungan JPK Jamsostek.
Sementara, tiga program lainnya mencakup lebih banyak pekerja yaitu sekitar 9 juta pekerja dan secara akumulatif mencapai hampir 20 juta tenaga kerja. Karena dinamika perusahaan, jumlah peserta Jamsostek di tiga program lainnya juga mengalami fluktuasi dan belum pernah mencapai seluruh tenaga kerja di sektor formal selarna 20 tahun beroperasi. Kendala besar yang dihadapi program Jamsostek adalah seringnya karyawan berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sehingga menyulitkan pendataan peserta. Sistem informasi dengan identitas tunggal juga belum berjalan dengan baik, sehingga sulit melacak karyawan yang berhenti bekerja, bekerja lagi di perusahaan lain, tetapi tidak melapor. Kendala lain adalah tidak adanya kewenangan penegakan hukum pada PT (Persero) Jamsostek membuat program Jamsostek tidak seperti yang diharapkan. Sebagai pemisahaan (meskipun persero) yang berbasis hukum privat, kewenangan penegakan hukum tidak dibenarkan. Penegakan hukum hanya boleh dimiliki badan hukum publik. Itulah sebabnya, UU BPJS mengubah PT (Persero) Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Namun sejarah Panjang jasa asuransi di Indonesia tersebut juga diwarnai berbagai stigma buruk tentang bisnis asuransi di mata masyarakat. Berdasarkan catatan data, nasabah asuransi sering mengalami kekecewaan dalam mengajukan klaim asuransi. Kekecewaan itu muncul bukan tanpa sebab. Banyak kasus pengajuan klaim asuransi oleh nasabah sering dimenangkan oleh perusahaan asuransi sehingga mereka bebas dari melakukan pembayaran pertanggungan. Dari data Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang didirikan dan ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Maret 2019 saja telah ada laporan 276 kasus klaim nasabah asuransi umum, dan 226 kasus klaim nasabah asuransi jiwa. Tercatat dari upaya mediasi, ada 118 klaim asuransi umum diterima dan 119 klaim ditolak. Sementara dari upaya ajudikasi, terdapat kurang lebih 27 klaim diterima dan 12 klaim ditolak.
Dari kesekian klaim risiko asuransi umum, kecenderungan klaim yang diterima dan ditolak mencapai rasio 50:50. Sementara dalam kasus klaim asuransi lainnya, mayoritas klaim sering dimenangkan oleh pihak penanggung (perusahaan).
Latar belakang penolakan klaim ini yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan polis yang dimilikinya. Kebanyakan peserta hanya mengajukan klaim asuransi jiwa dan harta benda. Contoh asuransi harta benda : produk asuransi yang menjamin kerusakan dan kerugian harta benda akibat kebakaran, bencana alam atau kejadian insidental. Biasanya, nasabah langsung mengajukan ganti rugi meminta pembayaran klaim begitu musibah terjadi. Sementara ketentuan pada polis tidak diperhatikannya.
Akibatnya, klaim ditolak perusahaan. Contoh, ketentuan pada polis asuransi harta benda mengatur bahwa rumah yang diasuransikan merupakan lokasi tinggal. Begitu perusahaan melakukan pengecekan, ternyata rumah tersebut dipergunakan sebagai bengkel. Peralihan fungsi semacam dapat berakibat pada penolakan klaim oleh perusahaan. Sebab kedua, kadang dokumen nasabah tidak lengkap.
Terlepas dari stigma dan hal-hal yang melatarbelakanginya seperti diuraikan diatas, realitanya sudah terdapat beberapa instrumen hukum yang dibuat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen jasa asuransi, dari instrumen hukum yang sifatnya umum sampai khusus spesifik mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dan konsumen jasa asuransi. Diantaranya dengan dibentuknya BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia) pada tanggal 12 Mei 2006. BMAI didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakkan hak-hak Tertanggung atau Pemegang Polis melalui proses Mediasi dan Ajudikasi. BMAI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang antara Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi). Tertanggung atau Pemegang Polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh Penanggung (Perusahaan Asuransi).
Selanjutnya berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya kedudukan BPKN dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen.
Selain itu juga dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka upaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat baik pelaku usaha ataupun konsumen, yang dibentuk disetiap kabupaten dan kota guna dapat menjangkau masyarakat lebih dekat yang diharapkan juga mampu menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen secara lebih sederhana, cepat, dan efisien.
Instrumen-instrumen hukum yang telah ada sekarang ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen jasa asuransi sudah cukup banyak dan berlapis. yang menjadi catatan untuk keperluan perbaikan yang urgent adalah upaya-upaya nyata dari institusi-institusi yang diberikan tugas oleh undang-undang untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pengetahuan tentang perasuransian serta hak dan kewajibannya selaku konsumen dan calon konsumen, begitupun para pelaku usaha bidang jasa asuransi juga mempunyai tangungjawab yang tinggi untuk memberikan pengetahuan dan edukasi tentang perasuransian, kejujuran dan transparansi informasi kepada konsumen dan calon konsumennya, serta mampu mencetak atau bekerjasama dengan tenaga-tenaga pemasar yang berkualitas baik secara keterampilan maupun moralitas.
Disamping itu masyarakat selaku konsumen dan calon konsumen jasa asuransi harus senantiasa waspada dan memiliki sifat pembelajar yang selalu mempunyai kemauan untuk terus belajar serta menambah wawasannya. Dengan demikian terjalin keseimbangan yang ideal dan harmonis diantara pelaku usaha asuransi dan konsumen jasa asuransi, serta negara dalam hal ini pemerintah yang mampu menciptakan instrumen hukum yang cukup memadai didukung oleh aparat penegak hukum yang memegang teguh ethos kerja dan moralitas yang tinggi.
Dari berbagai sumber